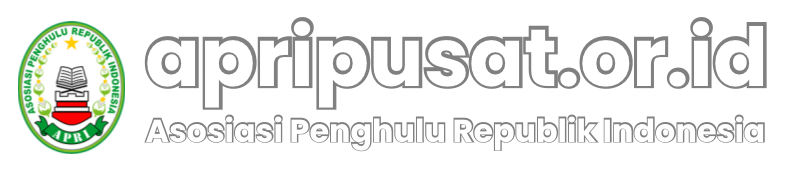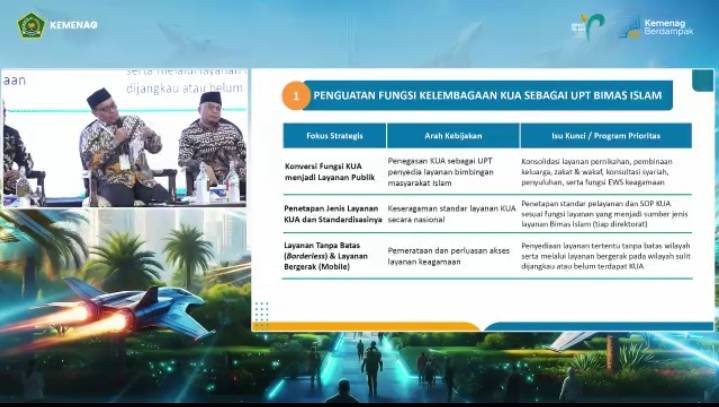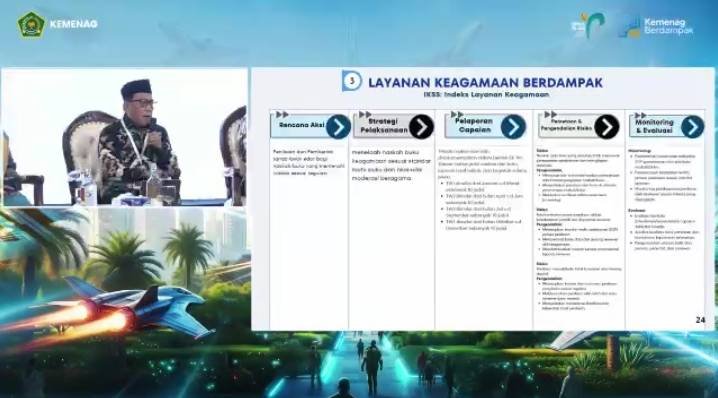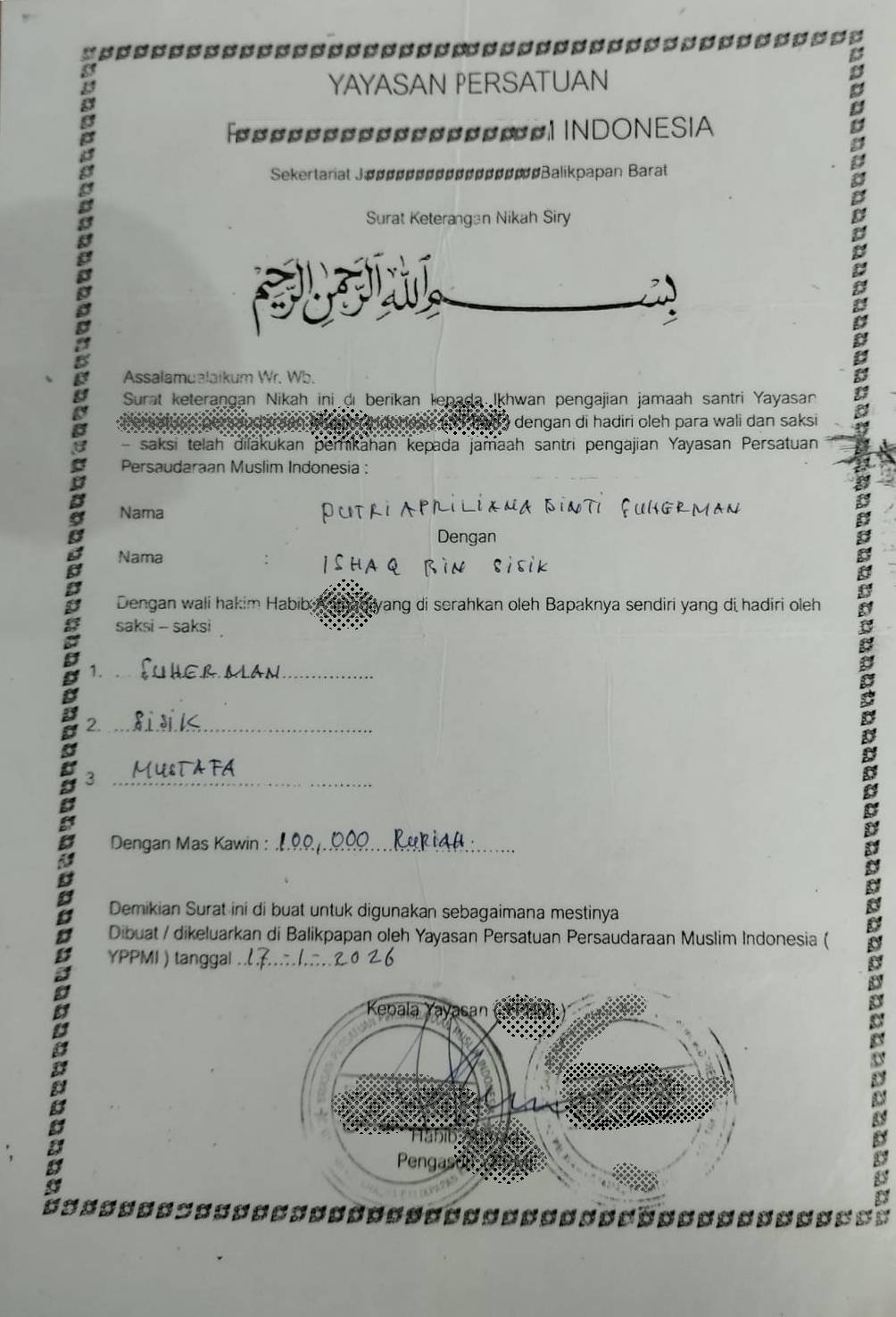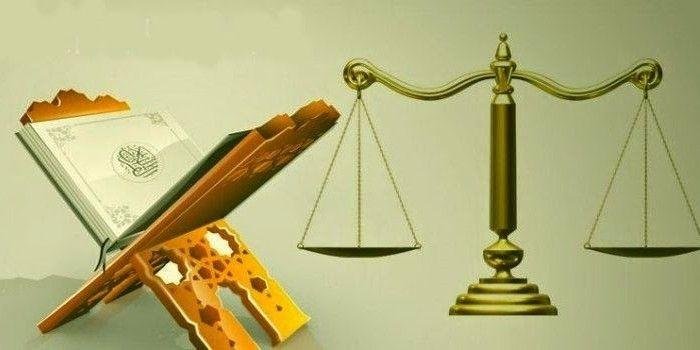
Kesaktian KHI: Kompromi Pandangan Fuqaha Tentang Kawin Hamil
03 Sep 2025 | 468 | Penulis : APRI mBanjar | Publisher : Biro Humas APRI Jawa Tengah
M. Sultan Latif Rahmatulloh
CPNS Penghulu KUA Karangkobar Kabupaten Banjarnegara
Di panggung hukum Islam di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tampil bak “penengah bijak” di tengah riuh perbedaan pendapat para fuqaha. Salah satu isu yang memantik perdebatan klasik sekaligus memancing adrenalin intelektual adalah hukum perkawinan wanita hamil karena zina. Di satu sisi, sebagian fuqaha memandang pernikahan semacam ini problematis bahkan tak sah karena kehamilan tersebut lahir dari hubungan di luar pernikahan yang dianggap meruntuhkan moralitas. Di sisi lain, ada pula ulama yang mengambil sikap lebih longgar dengan pertimbangan maslahah dan legitimasi sosial.
Nah, di sinilah KHI hadir seperti wasit yang membawa peluit kompromi. Dengan gaya khasnya yang memadukan fiqh, hukum positif, dan konteks sosial-keindonesiaan, KHI mencoba mencari jalan tengah agar hukum tidak hanya tegak di atas teks, tetapi juga berpijak pada realitas umat. Kesaktian KHI bukan sekadar soal “legalitas hitam-putih”, melainkan kemampuannya menyatukan suara-suara berbeda dalam satu naskah hukum yang resmi diakui negara.
Persoalan nikah wanita hamil karena zina, pada akhirnya bukan hanya perkara halal-haram, sah-batal, atau dosa-pahala semata. Ia adalah potret bagaimana hukum Islam bernegosiasi dengan zaman, bagaimana teks klasik berjumpa dengan problem kontemporer, dan bagaimana KHI mencoba memadukan keduanya tanpa membuat salah satu pihak dianggap “kalah”.
Beda Pandangan Fuqaha tentang Nikah Wanita Hamil karena Zina
Pandangan pertama dari ulama hanafiyah, madzhab ini menganggap bahwa hukum menikahi wanita dalam kondisi hamil karena zina adalah sah. Alasannya selama wanita itu bukan bagian dari mahram (wanita yang haram dinikahi) sebagaimana yang terdapat dalam QS. An-Nisa’: 22-24 maka diperbolehkan untuk dilangsungkan pernikahan.
Namun tidak sesederhana itu, Az-Zuhaily (2002) menyatakan bahwa yang berhak menikahi wanita hamil karena zina adalah laki-laki yang menghamilinya. Nah, dalam kasus ini ulama hanafiyah berbeda pandangan terkait hukum bagaimana jika yang menikahinya adalah bukan laki-laki yang menghamilinya? Penulis akan mencoba menjawabnya dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
Millah & Jahar (2019) menyebutkan bahwa ulama hanafiyah memiliki dua pandangan terkait pertanyaan tersebut. Ualama golongan pertama menganggap sah-sah saja jika yang menikahi bukan laki-laki yang menghamilinya dengan alasan selama masa hamil tidak boleh disetubuhi, sedangkan ulama kedua berpendapat bahwa haram hukumya jika bukan laki-laki yang menghamilinya.
Pandangan kedua dari ulama malikiyah sangat jelas dan lugas, yaitu tidak sah hukumnya pernikahan seorang wanita yang hamil karena zina. Kecuali bayi dalam kandungan telah dilahirkan. Pendapat ini juga dikutip oleh Millah & Jahar (2019) yang menyatakan secara lugas bahwa ulama malikiyah hanya membolehkan pernikahan wanita hamil sebab zina setelah ia dinyatakan bersih (istibra’) atau bayi tersebut telah dilahirkan.
Kita beranjak pada pandangan yang ketiga, masih merujuk pada Wahbah Az-Zuhaily yang menyebutkan bahwa Ulama Syafi’iyah mengesahkan pernikahan wanita hamil sebab zina dengan lelaki yang menghamilinya ataupun selainnya. Bahkan menyutubuhinya tatkala masih mengandung pasca pernikahan pun diperbolehkan, meskipun sebagian kelompok madzhab Syafi’iyah menganggap makruh.
Keempat, berbeda dengan pandangan sebelumnya, Ulama Hanabilah berpendapat tidak sah bagi lelaki menikahi wanita yang sedang hamil karena zina. Kecuali setelah melahirkan, dan ada satu syarat lagi yaitu si wanita telah bertaubat pada Tuhannya. Karena ketika ia belum bertaubat dari perbuatan zinanya maka masih dihukumi sebagai seorang pezina begitupun sebaliknya.
KHI dan Upaya Kompromi
Setelah menikmati perdebatan di atas, akhirnya kita telah sampai ke depan pintu gerbang pembahasan utama. Kenapa saya menganggap KHI sakti? Coba bayangkan KHI sebagai sebuah rujukan hukum Islam resmi di Indonesia harus mampu mengakomodir perbedaan pandangan para fuqaha sekaligus dihadapkan dengan konteks sosio-kultural di Indonesia yang sangat beragam.
Belum lagi KHI diletakkan ditengah-tengah banyaknya perbedaan penafsiran agama di Indonesia. Ada yang model beragamanya condong ke kanan, ada yang santuy ada juga yang nyelneh. Senyelneh ‘Bunuh diri dianggap Jihad’ atau senyelneh ‘Jumatan boleh via Zoom Meeting’, ya sudahlah.
Baik, kita kembali kepada persoalan. Terkait hukum pernikahan wanita hamil karena zina, termaktub dalam KHI pada bab VIII berjudul “Kawin Hamil” pasal 53. Secara tekstual dibunyikan dengan: (1) Seorang wanita yang hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya; (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya; (3) dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan lagi perkawainan ulang setelah anak yang dikandung itu lahir.
Pasal ini sebenarnya merupakan jawaban hukum terhadap drama biologis yang kerap kali mendahului legalitas formal sebuah hubungan. Ayat pertama berbunyi bahwa seorang perempuan yang hamil di luar ikatan pernikahan boleh (secara hukum) dinikahkan dengan lelaki yang menghamilinya.
Di balik bahasa yang terlihat sederhana ini, tersimpan pesan moral sekaligus sosial. Negara tidak hendak memutus tali tanggung jawab si lelaki karena perbuatan itu terjadi sebelum akad. Dalam bahasa lain, ini semacam “jalan pulang” agar urusan biologis dan sosial bisa bertemu di bawah satu payung yaitu perkawinan yang sah.
Pada ayat yang berbunyi 1) Seorang wanita yang hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya; KHI sepertinya sudah jelas poisisinya, bahwa Wanita hamil karena zina sah untuk melangsungkan pernikahan meskipun bayi tersebut belum dilahirkan. KHI tampaknya sedang memainkan dua nada sekaligus yaitu nada kehati-hatian yang serius dan nada kelonggaran yang agak santai.
Di sinilah letak persoalannya, apakah perempuan hamil di luar nikah hanya boleh dinikahi si aktor utama alias lelaki yang menghamilinya? Atau boleh juga oleh pemeran pengganti? Sekilas, kita cenderung mengira jawabannya: “ya, hanya si penghamil lah yang sah!”
Tapi tunggu dulu. Irfan (2013) dalam Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam memberi kita kacamata yang berbeda. Menurutnya, diksi “dapat” pada ayat 1 pasal 53 bukan sekadar kata sambil lalu. Kata ini justru membuka pintu kemungkinan bahwa lelaki lain, selain si penghamil, juga bisa masuk sebagai kandidat suami. Di sinilah KHI jadi menarik seolah-olah ia berkata: “Hey, jangan buru-buru menyimpulkan. Hukum punya banyak pintu masuk.”
Lalu, mari kita bergeser sebentar ke KBBI. Kata “dapat” di sana diterjemahkan simpel “mampu atau sanggup.” Lalu kalau kita lempar ke kamus hukum internasional, kata can muncul, dan ia membawa makna yang lebih garang: “memiliki kekuatan atau wewenang hukum untuk bertindak, bukan sekadar kemampuan fisik semata.” Jadi, can di sini bukan cuma “bisa,” tapi “punya legitimasi.”
Artinya? Bunyi ayat pertama bisa dipahami begini “kalau mampu maka nikahkan dengan lelaki yang mengamilinya”. Tapi kalau dia lari entah ke mana, hukum tidak menutup pintu bagi lelaki lain yang mau bertanggung jawab. Bahkan Irfan (2013) cukup berani menyimpulkanm, ayat ini sebenarnya bisa saja berbunyi, “Seorang wanita hamil di luar nikah dapat tidak dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.”
Pertanyaan berikutnya kemudian muncul, mengapa para perumus KHI memilih diksi “dapat” yang di mata sebagian cendekiawan dianggap ambiguitas? Kenapa tidak sekalian saja memakai kata yang tegas seperti “sah” atau “tidak sah,” biar jelas, tanpa ruang tafsir yang berliku-liku? Nah, di sinilah letak kesaktian KHI. Ia seperti sengaja bermain di wilayah abu-abu, bukan karena ragu, tapi karena sadar realitas jarang sekali jelas antara hitam-putih.
Sejak awal, KHI memang diposisikan sebagai jembatan emas yang berusaha mengawinkan aneka pandangan para fuqaha yang sering kali berbeda-beda. Tak cukup sampai di situ, KHI juga harus bersalaman dengan realitas ke-Indonesiaan yang super kompleks, adat yang berlapis-lapis, hukum yang berjejaring, dan keragaman tafsir keagamaan yang nyaris tak ada habisnya. Jadi, pilihan kata “dapat” itu bukan kelemahan, melainkan strategi, sebuah fleksibilitas hukum tapi tidak menutup pintu bagi keragaman konteks.
KHI sejatinya sedang memberikan langkah antisipatif, dalam realitasnya wanita hamil tidak selalu diakibatkan karena hubungan suka sama suka. Bahkan banyak terjadi wanita hamil karena sebab pemerkosaan, atau korban kebejatan dari laki-laki berhidung belang. Lalu coba anda bayangkan betapa na’asnya nasib wanita dan anak tersebut jikalau hanya boleh dinikahkan dengan lelaki yang menghamilinya.
KHI sebagai payung hukum ingin memastikan bahwa setiap jiwa yang lahir di dunia ini mendapat hak dan keadilan. Ini adalah spirit yang sejati, sebagaimana yang disebutkan oleh Mahfud MD bahwa “Produk hukum harus mempertimbangkan keadilan dan manfaat, tidak hanya kepastian.” Bagaimana menurut kalian?
Sumber gambar: https://baladena.id/paradigma-hukum-dalam-positivisme-dan-hukum-islam/
penulis adalah CPNS Penghulu pada KUA Karangkobar Banjarnegara Jateng